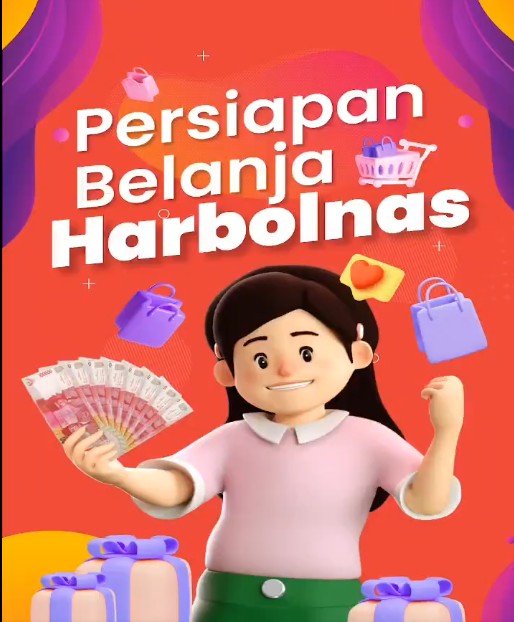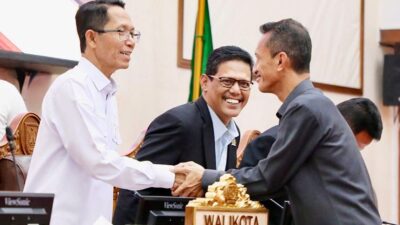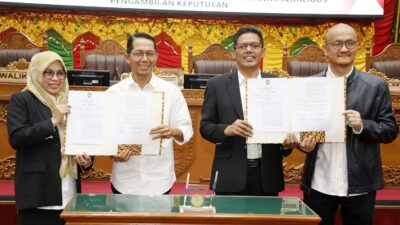Intuisi.net – Di era digital yang serba instan dan visual, budaya konsumtif tumbuh subur bagai candu. Diskon online, tren fashion, gadget terbaru, hingga “haul” belanja menjadi pemandangan sehari-hari di media sosial. Generasi muda, yang menjadi motor utama fenomena ini, sering kali membeli bukan karena kebutuhan, melainkan dorongan untuk terlihat “trendy” dan diterima. Media sosial, dengan segala kemegahan gaya hidup influencer, memperparah situasi ini, menciptakan ilusi bahwa kepemilikan barang menentukan status sosial.
Sayangnya, budaya konsumtif ini bukan sekadar soal gaya hidup, melainkan tekanan sosial yang nyata. Banyak anak muda merasa wajib memiliki barang branded atau gadget canggih agar dianggap relevan di lingkungannya. Tak jarang, demi menjaga penampilan, mereka rela berutang melalui kredit online, memalsukan gaya hidup, bahkan mengorbankan kebutuhan primer seperti biaya pendidikan atau kesehatan. Data dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa utang konsumtif masyarakat Indonesia melonjak hingga 15% dalam dua tahun terakhir, dengan mayoritas didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z.
Fenomena ini juga menggerus kesehatan keuangan keluarga. Banyak masyarakat, terutama di perkotaan, memprioritaskan konsumsi jangka pendek—seperti pakaian, gadget, atau liburan—ketimbang menabung atau berinvestasi. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022, hanya 38% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan memadai, dan kurang dari 20% memiliki dana darurat. Akibatnya, ketika krisis seperti pandemi atau kehilangan pekerjaan melanda, banyak keluarga terjebak dalam kesulitan finansial.
Yang lebih memprihatinkan, budaya konsumtif kini dikaitkan dengan nilai diri. Semakin banyak barang bermerek yang dimiliki, semakin seseorang dianggap “berhasil” atau “berharga”. Padahal, nilai sejati seseorang terletak pada integritas, pengetahuan, dan kontribusinya bagi masyarakat, bukan pada logo di tas atau ponsel yang digunakan. Psikolog sosial Dr. Risa Santoso menyebut fenomena ini sebagai “materialisme digital”, di mana media sosial memperkuat persepsi bahwa kepemilikan barang adalah cerminan identitas.
Untuk melawan candu konsumtif ini, diperlukan revolusi menuju konsumsi bijak. Pertama, literasi keuangan harus digencarkan melalui pendidikan formal dan kampanye publik. Sekolah dan komunitas dapat mengajarkan cara menyusun anggaran, berinvestasi, dan membedakan kebutuhan dari keinginan. Kedua, media sosial harus dimanfaatkan untuk mempromosikan gaya hidup minimalis dan berkelanjutan, seperti mendaur ulang barang, mendukung produk lokal, atau memilih kualitas daripada kuantitas. Ketiga, individu perlu membangun kesadaran diri bahwa nilai personal tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, melainkan oleh apa yang dilakukan untuk dunia.
Pemerintah juga memiliki peran krusial. Regulasi kredit online perlu diperketat untuk mencegah jebakan utang konsumtif, sementara insentif untuk menabung atau berinvestasi harus diperluas. Komunitas lokal dapat mengadakan lokakarya tentang pengelolaan keuangan atau mendirikan platform barter untuk mengurangi konsumsi berlebihan. Sebagai individu, langkah sederhana seperti membuat daftar belanja, menunda pembelian impulsif selama 24 jam, atau bertanya, “Apakah ini benar-benar saya butuhkan?” dapat menjadi awal perubahan.
Sudah saatnya kita memutus rantai candu konsumtif ini. Hidup bukan tentang siapa yang paling banyak belanja, melainkan siapa yang mampu mengelola dan memaknai apa yang dimiliki. Dengan konsumsi bijak, kita tidak hanya menyelamatkan dompet, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih sadar, berkelanjutan, dan bermartabat.